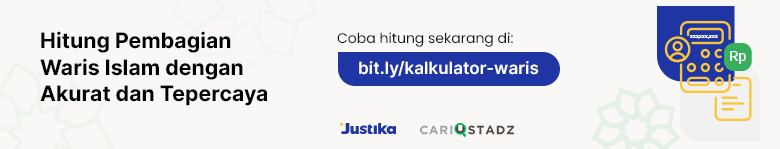Dalam kehidupan, manusia tidak sekadar lahir, tumbuh, beraktivitas, lalu mati meninggalkan dunia. Hidup bukan hanya tentang menjalani hari, tetapi juga tentang memberi makna dan manfaat. Semua itu bermula dari kesadaran untuk merenung dan melihat kembali ke dalam diri apa yang sudah dilakukan, dan apa yang sedang dipersiapkan?
Itulah sebabnya, Al-Qur’an mengingatkan manusia melalui Surah Adz-Dzariyat ayat 21:
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
“Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”
Ayat ini menjadi ajakan untuk berhenti sejenak dan memperhatikan diri. Ada begitu banyak karunia Tuhan yang telah diberikan, dan semua itu seharusnya mengarahkan kita pada hidup yang lebih terarah dengan akal yang jernih dan hati yang sadar.
Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya refleksi diri dalam sebuah hadits:
الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
“Orang yang cerdas adalah yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati.” (HR. Tirmidzi)
Dengan kata lain, kecerdasan sejati bukan hanya soal pengetahuan, tapi tentang kesadaran untuk menata hidup, mempersiapkan bekal, dan tidak larut dalam rutinitas tanpa arah.
Mengapa penting merenung dan mengoreksi diri? Sebab muhasabah adalah jalan untuk menyadarkan hati agar tetap berjalan pada lorong yang terang. Ia menjadi cara agar hidup tidak kehilangan arah, agar kita bisa terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas sebagai hamba.
Pertama, apakah kita mengenal Allah hanya sebatas hafalan, atau sudah hadir dalam pengalaman dan pengamalan hidup sehari-hari?
Kita mungkin tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun (Al-Ghaffar), tapi seberapa sering kita benar-benar peduli terhadap dosa-dosa yang kita lakukan? Kadang kita larut dalam kemaksiatan, merasa biasa saja, tanpa pernah sungguh-sungguh menyadari bahwa ada begitu banyak dosa yang seharusnya kita bawa ke hadapan Allah untuk ditaubatkan.
Kita juga tahu bahwa Allah adalah Pengatur hidup dan Pemberi rezeki (Rabbul ‘Alamin, Ar-Razzaq). Tapi seberapa dalam pengetahuan itu benar-benar hadir dalam keyakinan dan sikap kita? Tak jarang, kita justru lebih sibuk membandingkan hidup dengan milik orang lain. Kita mengukur kebahagiaan berdasarkan apa yang dimiliki orang lain, dan lupa bahwa karunia Allah yang ada pada diri sendiri sering kali jauh lebih besar hanya saja tak kita syukuri.
Kedua, apakah kekhawatiran kita terhadap kehilangan dunia lebih besar daripada kehilangan arah menuju Allah?
Hidup memang menuntut usaha. Kita bekerja, belajar, dan berjuang demi masa depan. Namun, jangan sampai segala aktivitas itu justru menenggelamkan tujuan utama hidup yaitu mengingat Allah dan kembali kepada-Nya.
Kewajiban manusia adalah mengingat Tuhannya. Sementara usaha mempertahankan hidup adalah bagian dari tanggung jawab, tapi bukan prioritas utama. Jangan-jangan kita lebih resah memikirkan nasib, karier, atau jabatan di masa depan, daripada khawatir akan seperti apa nasib kita kelak di hadapan Tuhan.
Allah mengingatkan dengan tegas dalam Surah Ṭāhā ayat 124:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta.”
Inilah renungan penting, bisa jadi tanpa sadar kita lebih takut kehilangan dunia, daripada kehilangan arah menuju Allah. Itulah sebabnya, dalam setiap rakaat salat, kita berdoa hingga 17 kali dalam sehari:
اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
“Tunjukilah kami jalan yang lurus.”
Sebuah pengakuan bahwa kita butuh bimbingan, agar tidak tersesat dalam kehidupan yang begitu cepat berubah.
Syekh Abdul Qadir al-Jilani pernah menasihati:
“وَيْلٌ لِمَنْ إِذَا فَاتَتْهُ الدُّنْيَا بَكَى، وَإِذَا فَاتَهُ اللَّهُ لَمْ يَشْعُرْ.
“Celakalah orang yang jika kehilangan dunia ia menangis, tetapi saat kehilangan Allah, ia bahkan tidak merasa.”
Ketiga, apakah kita hidup dan beragama tumbuh dalam iman, atau hanya terjebak dalam rutinitas dan ritual semata?
Pertanyaan ini layak diajukan kepada hati kita masing-masing. Bisa jadi, kita rajin salat berjamaah, rutin bangun di sepertiga malam, bahkan istiqamah berpuasa Senin dan Kamis. Tapi jika semua itu tidak menjadikan kita lebih peduli terhadap sesama, lebih empati terhadap penderitaan orang lain, maka mungkin yang tumbuh hanya kebiasaan, bukan keimanan.
Allah memperingatkan dengan keras dalam Al-Qur’an:
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
“Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya.”
(Surah Al-Ma’un: 4–5)
Ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak salat, tapi kepada mereka yang salat namun kehilangan makna dalam ibadahnya. Salat menjadi rutinitas, bukan lagi jalan untuk tumbuh dan terhubung dengan Allah.
Pada akhirnya, bisa saja kita sibuk dengan ibadah, tapi tidak tumbuh dalam iman. Padahal buah sejati dari iman bukan hanya di sajadah, tapi dalam akhlak, kepedulian sosial, dan kasih sayang yang nyata.
Jalaluddin Rumi pernah berkata:
“Engkau tak perlu mencari Tuhanmu di langit. Carilah Dia di bumi, di antara mereka yang lemah. Bagaimana mungkin Allah menyayangimu, jika engkau sendiri tidak menyayangi makhluk-Nya?”
Mabrur Inwan, M.Ag, Ustadz di Cariustadz
Tertarik mengundang Mabrur Inwan, M.Ag? Silakan Klik disini.