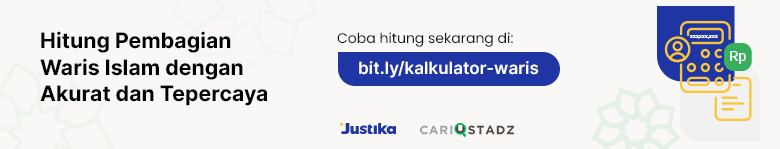“Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu.” Demikian pesan Allah kepada hamba-Nya dalam QS. an-Nahl: 43 dan al-Anbiya’: 7. Saat membaca ayat ini, biasanya muncul pertanyaan “Kenapa kok ahli dzikir dan bukan ahli ilmu ya?”. Sekilas, arahan Al-Qur’an ini terkesan keliru. Pasalnya, bertanya kepada mereka yang berilmu menjadi kelaziman yang tidak terbantahkan.
Namun Al-Qur’an lebih memilih ahli dzikir yang identik dengan sosok religius yang terkadang tidak banyak ilmunya. Mengapa demikian? Sebagai awalan, kita pasti setuju bahwa betapa banyak kerusakan alam raya dan tatanan sosial yang diakibatkan orang berilmu yang tidak memiliki iman. Ada beberapa hal dibalik pemilihan ahli dzikir tersebut yang menarik untuk diperhatikan.
Konteks ayat
Saat membaca QS. an-Nahl: 43 dan al-Anbiya’: 7, kita akan mendapati bahwa perintah bertanya ini didahului pembahasan seputar pengutusan rasul sebelum Nabi Muhammad. Hal ini berarti pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari ruang lingkup keimanan yang memiliki sumber dan jalur berbeda dengan ilmu pengetahuan yang dikenal dewasa ini. Jika sumber dan jalur ilmu adalah logika dan pengamatan alam raya, maka keimanan sumbernya adalah hati yang bersih dengan jalur informasi ‘wahyu’. Bagi ahlus sunnah, informasi dari keduanya menjadi ilmu pengetahuan yang sama kuatnya dan tidak perlu dipertentangkan.
Memang, saat ini ilmu yang bersumber dari logika lebih dominan daripada ilmu yang bersumber pada ‘wahyu’. Namun demikian, tidak jarang logika terbentur dengan kebuntuan dalam memecahkan masalah. Betapa banyak ilmuwan muslim yang mendapatkan jawaban dari kebuntuan mereka melalui mimpi? Realita kehidupan yang logika tidak mampu menyentuhnya. Ini artinya, peran kebersihan hati jauh lebih kuat daripada kecerdasan logika.
Ulul albab
Berilmu saja tidak cukup. Ia harus disertai keimanan. Setidaknya, dalam dua tempat Al-Qur’an memuji orang mukmin yang berilmu; QS. al-Mujadilah: 11 dan QS. Ali ‘Imran: 191. Jika dalam ayat pertama mereka disebutkan dengan iman dan ilmu, maka dalam ayat kedua mereka diidentikkan dengan proses memperoleh keimanan dan ilmu tersebut. Yakni – tutur ayat kedua – golongan yang mengingat Allah dalam kondisi apapun sembari memperhatikan ciptaan-Nya. Hingga kebiasaannya ini mengantarkan mereka pada pengakuan akan kemahakuasaan dan kesempurnaan Tuhan. Mereka digelari dengan sebutan ulul albab.
Yang menarik adalah penyebutan iman didahulukan dari penyebutan ilmu, baik secara gamblang dalam ayat pertama mapun proses perolehannya dalam ayat kedua. Dari penyebutan ini, secara tidak langsung Al-Qur’an lebih mengutamakan ahli dzikir daripada ahli pikir. Sebab, ahli pikir yang tidak didasari dzikir akan mengantarkan mereka pada jurang ke-aku-an yang menafikan peran Tuhan. Mereka akan semakin jauh dari-Nya sampai tidak terlihat dan pada akhirnya tidak mengakui keberadaan-Nya. Inilah yang dikehendaki oleh setan musuh abadi anak Adam.
Yang lebih menarik lagi adalah penyebutan ulul albab yang menggambarkan perpaduan iman dan ilmu ini menjadi takhsis bagi yatadzakkaru. Aktivitas yang disebutkan pada akhir ayat QS. Ali ‘Imran: 190 ini seakar dengan kata dzikir. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa tempat bertanya yang tepat adalah orang yang memiliki iman dan ilmu atau ulul albab. Dengan ilmu, mereka akan memberitahu aneka jawaban yang ada dari persoalan yang diajukan. Sedangkan dengan keimanan, mereka akan menunjukkan jawaban sekaligus memberikan arahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi penanya.
Kisah Nabi Musa dan hamba yang salih
Imam Mutawalli asy-Sya’rawi saat bertemu ayat ‘pencarian tuhan’ oleh Nabi Ibrahim, mengawalinya dengan penjelasan dua kerajaan; al-mulk dan al-malakut. Yang pertama terulang sebanyak 47 kali dalam Al-Qur’an. Sementara yang kedua hanya 4 kali saja. Al-mulk – sebagaimana tutur Imam asy-Sya’rawi – merupakan kerajaan yang didapati oleh mereka yang berpikir di balik sesuatu yang kasat mata. Sesuatu yang bisa diketahui melalui panca indera. Sedangkan al-malakut adalah sesuatu yang tidak tampak baginya atau berada di balik al-mulk tadi. Dengan kata lain, al-mulk adalah wilayah yang bisa diketahui dengan panca indera atau raga. Sementra al-malakut hanya bisa diketahui dengan keimanan atau jiwa karena ia lebih sebagai bentuk hakikat sesuatu.
Pengalaman al-mulk dan al-malakut ini bisa kita temukan pada kisah perjalanan dua sosok mulia, yakni Nabi Musa dan hamba pilihan Allah, yang diabadikan dalam surat al-Kahfi. Sebagai seorang rasul, Nabi Musa tentu sangat berpegang pada syari’at yang menjadi pokok risalahnya. Sementara itu, hamba pilihan Allah tadi – yakni Nabi Khidir menurut pendapat yang masyhur – adalah seseorang yang sangat teguh pada ajaran rasul sebelumnya. Sampai ia mendapat anugerah berupa ilmu laddunni. Dari anugerah yang luar biasa inilah, ia lebih berpegang pada isyarat daripada syari’at. Tolok ukur syari’at adalah sesuatu yang kasat mata atau al-mulk. Sementara isyarat biasanya lebih pada hakikat atau al-malakut.
Singkat cerita, jika perjalanan keduanya mengikuti pilihan Nabi Musa yang lebih condong pada al-mulk, boleh jadi akan terjadi perampasan kapal yang ditumpanginya, dosa besar seorang anak berikut sakit hati kedua orang tuanya, dan perampokan harta anak yatim oleh mereka yang bakhil dan rakus. Namun tiga hal itu tidak terjadi karena saat itu yang jadi pilihan adalah jalur al-malakut. Dari kisah ini bisa ditarik garis kesimpulan bahwa, jawaban ahli dzikir melampaui ahli ilmu. Ini tidak berarti bahwa Nabi Musa bukan ahli dzikir. Beliau seorang nabi rasul yang kedudukannya tentu melebihi hamba pilihan Allah tadi. Namun karena saat itu, Nabi Musa lebih berpegang pada sisi al-mulk saja.
Dzikir sumber ilmu
Banyak sekali cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana informasi ayat yang pertama kali turun (QS. al-‘Alaq: 4-5), ilmu pengetahuan bisa diperoleh melalui dua hal; dengan qalam atau melalui belajar dengan bantuan logika dan panca indera dan dengan jalur ‘wahyu’ yang datang langsung dari Allah. Yang pertama merupakan cara formal yang banyak ditempuh banyak orang. Hasilnya pun tidak jauh dari apa yang dipelajari. Sementara cara kedua menjadi cara instan yang hanya bisa diraih oleh mereka yang memiliki komitmen tinggi terhadap manhaj Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan aneka perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam bahasa sederhana, mereka adalah orang yang bertakwa.
Melalui QS. al-Baqarah: 282 Allah menutup ketentuan hutang piutang dengan perintah bertakwa. Sebagai konekuensi perintah-Nya dalam ayat tersebut, Dia akan mengajarkan sesuatu secara langsung kepada mereka yang bertakwa. Seseorang hanya akan mampu konsisten dalam bertakwa jika Allah sudah bersemanyam di hatinya. Keberadaan Allah dalam hati bisa diperoleh melalui dzikir; baik dengan lisan, hati, atau keduanya. Jadi perintah bertanya kepada ahli dzikir ini tidaklah keliru. Karena sosok yang akan ditanya sudah dekat dengan Dzat Yang Mahatahu dan telah berjanji akan mengajarkan apapun kepadanya.
Demikian kurang lebih gambaran dari sekelumit jawaban dari teka teki dibalik perintah bertanya kepada ahli dzikir dan bukan ahli pikir. Selain bisa memberikan jawaban karena keluasan ilmunya (ulul albab) juga karena mereka memiliki sumber ilmu pengetahuan yang tidak terkira berkat ketakwaan mereka. Tentunya jawaban yang diberikan akan lebih tepat sasaran. Pasalnya tidak jarang ada motif negatif yang terselubung di balik pertanyaan yang dilontarkan. Ahli dzikir biasanya mampu melihat hal tersebut sehingga tujuan si penanya tidak tercapai. Atau bisa jadi jawaban dari pertanyaannya perlu tahapan-tahapan yang bisa menyelamatkannya dari kesesatan yang bisa muncul dari jawaban tersebut. Dari sini, ahli dzikir menjadi sosok yang tepat untuk bertanya. wallaahu a’lam… []
Syafi’ul Huda, S.Pd.I.,M.Ag., Ustadz di cariustadz.id
Tertarik mengundang Syafi’ul Huda, S.Pd.I.,M.Ag.? Silakan Klik disini